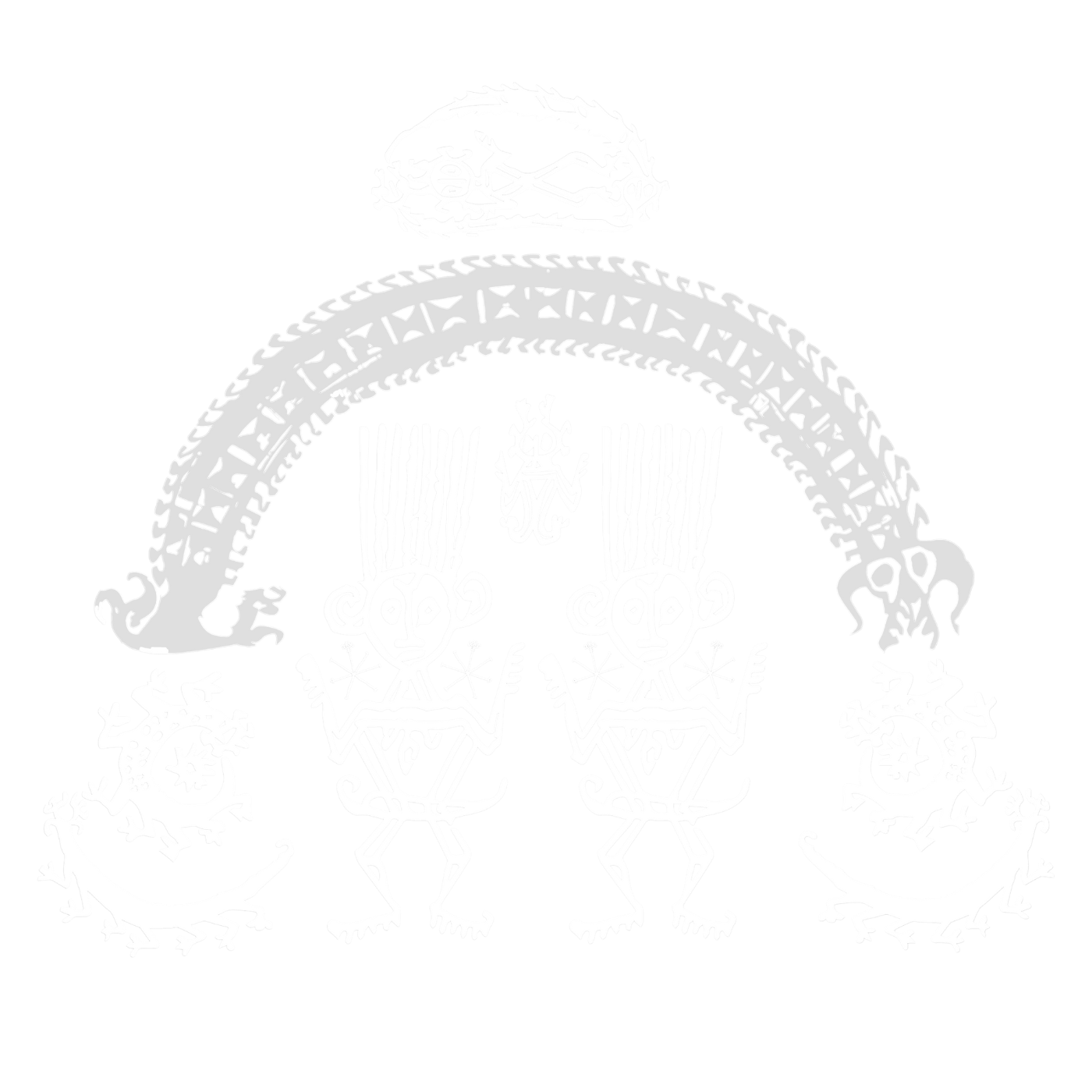Sianjur Mula Mula[1], di hari penguburan Oppungku[2], kulihat Mamak tidak lagi menangis, telah habis air matanya di Jakarta, paling-paling saat pertama kali ia melihat Bapaknya, Oppung doliku, ketika mobil yang kami tumpangi mengantar kami tepat di depan rumah, itu terakhir benar-benar kulihat Mamak menangis, menghampiri Oppungku, memeluknya, meratapi, bersenandung, menyampaikan puji-pujian dalam bahasa Toba yang aku pahami betul, bait-bait yang mengiringi tangisnya itu benar-benar mematahkan hatiku.
Tidak satupun kulihat darah margaku berada di rumah itu, bahkan Bapak—entah, tidak lagi kuingat kapan terakhir kali Aku memanggilnya begitu. Air mata Mamak terurai menjadi tulisan-tulisan di dalam kepalaku. Suaminya tidak mati, namun juga tidak mendampingi sajak tangisnya. Tidak mampu Aku merengkuhnya, aku membenci itu.
Adik perempuanku duduk bersama Mamak, ia menoleh ke arahku, ia juga telah habiskan air matanya, dua hari lalu masih jelas suara Oppungnya ketika menunggu makan malam di ujung telepon, tak ada yang dapat kutangkap maksud dari undangan kedua matanya itu.
“Lihatlah, betapa gagahnya engkau. Mengingatkanku ketika banyak gadis memujaku saat Kutunggangi kuda bapakku. Mempesona nian rambut panjangmu.” Ucap Oppung doli dalam bahasa Toba, beberapa hari lalu dipujinya Aku saat kami bertukar rindu lewat panggilan gambar. Suaranya masih kusimpan baik di ingatanku, tidak pernah kutemukan garis bibir paling tulus selain dari senyumannya, sepanjang aku menemui banyak manusia di dalam hidupku, gigi depannya sudahlah tanggal mengingat usianya, namun sorot kedua matanya tidak pernah kulihat ragu, masih begitu tajam, seperti pisau yang mampu menemui batas pada cahaya yang membutakannya, sampai sebelum ia menjemput keabadiannya.
Oppung doliku merupakan seorang yang pendiam, ketika ia mulai banyak bicara adalah saat ia memenuhi panggilan adat sebagai seorang pemimpin, menikahkan dan menghantar kematian orang lain, larut pada riwayat dan hikayat, serta bermain bersama cucu-cucunya. Kaki kanannya menjadi saksi bahwa ia adalah penunggang kuda di masa lalu, gagah, serta menegaskan kebijaksanaan yang ia miliki, juga bukan dari kalangan biasa.
“Jika tak dijemputnya aku menjadi istri bersama keluarga dan Amang[3] dari Bapakmu, masihlah dapat kunikmati menjadi tauke di kampung. Tapi, Atas nama Tuhan Allah Tritunggal, Aku bersyukur memilikimu, Agustus yang mati, dan adik perempuanmu.” Tegas Mamak. Berembun kedua matanya.
Mamak sudah mengalami banyak kehilangan, Anak keduanya, adik laki-lakiku Agustus, adik-adiknya, bapaknya, Suaminya yang entah pergi ke mana, dan Kesempatannya.
Menikah di usia yang begitu muda, membuatnya kehilangan banyak arus dalam waktu, jejak masa mudanya dihabiskan dengan menjadi Istri, dan seorang Ibu.
“Bagaimana rasanya menikah, Mak?” Tanyaku.
“Awalnya kau akan merasa seluruh dunia adalah milikmu, miliknya. Kemudian hanya akan tersisa rasa pahit, aku tidak bilang aku tidak beruntung bersuami, di luar sana tentu banyak yang berjalan dengan manis sampai datang senja mereka. Tetapi, banyak juga yang seperti Mamakmu ini, perempuan-perempuan yang hidup di antara berbagai warna.” Balasnya dengan bahasa Toba, aroma arsik memenuhi dapur.
Mamak memang rutin memasak arsik, olahan ikan mas khas batak yang cukup sering ditemui di wilayah Toba. Baginya, arsik merupakan simbol berkat, restu, serta harapan. Di dalamnya terdapat berbagai rempah yang kemudian membuat arsik ituberaroma kuat dan memiliki rasa yang unik, juga beragam.
Andaliman[4] dan Sirias[5], merupakan rempah yang membuat masakan khas Batak memiliki rasa yang berbeda dari wilayah lain.
Memasak adalah keahlian Mamak, bukan karena aku menganggap dapur sebagai wilayah perempuan, namun seperti setiap rempah dan bahan masakan yang ada di hadapannya, tidak pernah mengkhianati kedua tangan kasarnya itu. Aku paham kemudian jika ia mengatakan bahwa ia hidup di antara banyak warna, pengalamannya, hatinya, benar-benar membuatnya menghidupi setiap langkahnya, betul, memasak merupakan langkah di taman seribu bunga.
Dapur menjadi tempat di mana aku banyak menghabiskan waktu, bahkan banyak di antara buku-buku yang kumiliki tidak lagi beraroma kertas dan minyak mesin cetak, tetapi berbau rempah. Berkat dapur, aku mengenal Mamak sedalam kasih yang ia miliki, bukan sebagai seorang anak laki-lakinya, tetapi sebagai seorang Kawan.
Dari sana pula tempatku mulai menyukai rempah dan memasak, tentu, mungkin tidak sama dengan rasa yang masakan Mamak miliki. Dapur justru membuatku paham bagaimana menjadi seorang laki-laki, di saat banyak orang-orang seusiaku, bahkan di atas itu, menilai hanya perempuanlah yang boleh terima keringat berkat panas api dan membicarakan isi lemari di dapur, itu sebabnya mereka juga tidak mampu dekat dengan kehidupan para petani, dan apa yang sedang mereka hadapi, juga apa yang terjadi di setiap gubuk, bahkan kediaman mereka sendiri,
“Naiklah sudah harga cabai, pening kepalaku, pening juga tulang[6] dan oppung borumu.” Seru Mamak,
“Pemerintah dan tengkulak-tengkulak bajingan itu seperti berencana membunuh setiap orang di Sumatera” Lanjutnya. Bagi Mamak, cabai seperti jantung dari setiap sentuhan masakan orang Sumatera, capsaicin[7] yang menghantarkan rasa menantang untuk lidah,
jika dikatakan orang Sumatera memang memiliki kebahagiaan dalam setiap tantangan di hidup mereka, masakan-masakan orang Sumatera dapatlah dilihat sebagai salah satu hal yang memperkuat standar dan prasangka itu, orang-orang Sumatera berani memulai mengambil keputusan di dapur dan perapian, tempat belajar, dan menemukan diri mereka, juga sebagai tempat berhimpunnya api perlawanan di masa lalu, seorang Aceh yang baru saja menyantap habis Kuwah beulangong [8]mungkin mampu menundukkan sepuluh penjajah dengan rencong yang dimilikinya.
Mamak tidak suka memerintah, ia lebih memilih untuk melakukan berbagai hal sendirian jika ia mampu, bahkan dalam urusan-urusan yang tampaknya dilihat orang banyak sebagai tugas yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, ia bahkan tidak bergantung pada suaminya. Sejak lama ia telah menghidupi dirinya sendiri, bahkan ketika saat mengandungku, tak sedikitpun ia meletakkan harapan pada seseorang, terutama suaminya itu. Baginya, memberikan hidup pada orang lain merupakan sebuah bentuk pelecehan terhadap semesta, kehendak manusia sejatinya adalah tidak memberikan ruang pada orang lain untuk mengeja hakikat yang terdapat di langkah-langkah dan keputusan seseorang, baik yang berkaitan untuk dimaksudkan sebagai niat baik atau jahat sekalipun.
“Biarlah jalanku menjadi jalan anak perempuan yang tak elok.” Tegas Mamak dalam bahasa Toba. Awalnya kata-kata itu membuatku begitu heran, namun kemudian jika melihat sikap-sikap Mamak di kehidupannya, membuatku mempercayai kata-kata itu sebagai bentuk kasih yang digambarkannya melalui tindakan yang berterus terang, orang-orang akan melihatnya sebagai sesuatu yang menyalahi nilai-nilai di lingkungannya.
Pernah dalam satu waktu, Mamak mengirimkan beberapa karung beras ke sebuah acara amal di sebuah rumah ibadah di dekat rumah kami, orang-orang yang melihat itu mencibir dekat dengan telinga mereka, menurut mereka kegiatan amal itu tak seharusnya didatangi oleh wanita batak, yang juga berbeda tuntunan dari mereka,
“Jika kalian berkesempatan membaca tulisan-tulisan di karung beras itu, asal petani-petani yang merawat beras-beras ini adalah petani-petani yang menunggu tiga waktu ibadahnya dalam pekerjaan mereka di sawah, lalu apa yang salah dari itu?” Ucap Mamak ke salah satu pengurus acara itu, yang lain tak sedap memandang Mamak, aku melihat beberapa masih berbisik mengenai dirinya.
“Beras-beras ini pun akan jadi kotoran nantinya, kenapa tidak kalian persoalkan kotoran itu? Tambahnya, melihat ke arah kerumunan di dekat Mamak,
“Asrama tempat anak-anak menamatkan kitabnya butuh beras-beras ini, begitu juga dengan remaja-remaja di Panti. Saya yang akan membawanya jika tidak kalian terima.” Ucap seorang Imam,
seorang Sumatera yang kami kenal cukup lama, ia datang dari arah tempat menyucikan diri.
“Umak ini punya kewajiban, kewajiban sebagai tetangga, sebagai umat Tuhan, juga sebagai Manusia. Kalian persoalkan hal kecil itu?” Tambah sang Imam, orang-orang terdiam, tak ada satupun di antara mereka menyanggah ucapan imam itu, di angkatnya satu karung beras masuk ke dalam tempat yang menampung barang sumbangan, di angkatnya lagi karung ke dua, ke tiga, sampai habis karung-karung itu.
Mamak percaya, Tuhanlah yang memiliki, bukan manusia yang memiliki Tuhan. Oleh karena itu, Mamak bertentangan dengan konsep-konsep yang membatasi Kemanusiaan oleh karena perbedaan tuntunan, ia melihat itu sebagai konsep manusia yang termakan oleh perasaan kepuasan pada batas-batas, terutama batas Memanusiakan, sedangkan baginya, Kasih dan Kesukacitaan Tuhan pada manusia tidak memiliki konsep, begitu juga harusnya manusia menjalankan kasih dan kesukacitaan.
Itulah sebabnya pula, mamak tidak bergantung, terutama pada hukum, etika dan moralitas masyarakat yang membatasi, terlebih jika itu berkaitan dengan hajat orang banyak. Baginya, sikap melawan adalah sikap untuk hidup, itu juga yang membuatnya selalu mengatakan bahwa ia seutuhnya merupakan seorang Anak Perempuan, dan terus demikian, langkah yang ia pilih bertumpu pada gagasan dikala seorang anak perempuan yang tidak disukai karena jalannya yang tidak elok, sejatinya memiliki bunga kasih yang lebih bebas bertelanjang pada ketulusan, anak perempuan dilambangkannya sebagai bentuk tegas perlawanan kaum wanita, yang tidak bergantung pada mitos-mitos perempuan yang masyarakat ciptakan untuk mengkerdilkan jalan yang perempuan-perempuan pilih, Mamak katakan Anak Perempuanlah yang pertama mandiri sekalipun dilihat sebagai yang terkecil di dalam komunitas masyarakat.
Pandangan Mamak banyak mempengaruhiku, sebagai perempuan batak, ia terpenjara dalam statusnya, di keluarganya ia adalah Boru[9], anak perempuan yang hanya boleh bermanja pada Bapaknya yang dianggap sebagai raja[10] oleh keluarga suaminya, di keluarga Margaku, ia adalah Parumaen[11] yang wajib untuk patuh sekalipun ia adalah Boru sang raja, di kedua keluarga itu ia dibatasi secara sosial untuk memberikan pendapatnya karena ia adalah seorang Perempuan. Namun, hal itu justru yang membuatnya lebih tidak kenal takut, ia menentang tradisi yang membatasi manusia, terutama perempuan.
“Giliranku yang akan berterus terang, anak perempuannya inilah yang harus tetap berdiri di sebelah kanan Bapaknya. Aku pula yang pertama akan bicara pada jasad bapakku itu nanti, di antara cucu-cucunya biarlah sepupu perempuan tertua anakku yang didahulukan dalam pesta,” Bantah Mamak dalam bahasa Toba, ia menjadi panah wira bagi dirinya sendiri, masuk ke dalam majelis raja-raja[12]yang menyinggung persoalan kematian bapaknya, oppung doliku, ia katakan hal itu sebab raja-raja melihat perempuan, terutama yang telah bersuami adalah kepemilikan keluarga suami mereka, yang keterlibatannya tidak dibutuhkan, kecuali keringat perak dan emas yang mereka hasilkan, juga bagi sepupu-sepupu perempuanku.
Aku duduk di samping Oppung boruku, yang beberapa hari itu meratap, bersenandung kehilangan untuk suaminya, Oppung doliku. Melihat Mamak, sedikit memanaskan hatiku, sekali ada yang akan menghardiknya, mungkin akan kupertemukan mereka dengan belati pemberian oppungku, yang diberikannya di pintu masuk kandang babi di kampung beberapa tahun lalu, adik perempuanku berdiri menyenderkan kedua kakinya di punggungku, meninju kepalaku, ia curiga pada desis dari lengkungan bibirku. Majelis raja-raja itu berakhir beberapa saat, mereka menyetujui permintaan Mamak yang pertama, namun tidak dengan permintaannya yang lain, cucu perempuan dianggap mereka memiliki tempatnya sendiri,
“Ada yang ingin ku katakan pada Nantulang[13]ku.” Kata Pariban[14]ku di hadapan raja-raja di majelis itu, sepupu perempuanku, ia memiliki keresahan yang sama dengan Mamak, ditambah ia tak suka dengan istri adik bapaknya itu, jika ada yang mirip dengan Mamak adalah sepupu perempuanku itu. Adik perempuanku bukan tak ingin mengatakan apa-apa, ia lebih keras lagi, lebih keras dari Mamak, ia adalah bagian dari diriku yang lain.
Di majelis itu, ditentangnya mereka berdua, puluhan orang melihat ke arah mereka,
“Yang memiliki keresahan biarlah tumpah ruah, yang mati biarlah damai di kematiannya.” Kataku dengan tegas dalam bahasa Toba, membelai kepala Oppung doliku, ratusan pasang mata dengan kebisuan mereka mengarah padaku di majelis itu, mereka kenali aku,
“Bukankah seharusnya kau di belakang, Amang?” Ucap seorang raja yang tidak cukup mengenaliku di majelis itu, aku pun tak kenali dia,
“Aku di sini atas permintaan Oppung doliku, permintaannya adalah darah bagi langkahku yang berpindah,” Jawabku, bagi raja-raja, cucu laki-laki dari pihak boru seharusnya berada di dapur, bahkan lebih ke belakang lagi, bersama bapak mereka, namun mereka yang cukup mengenalku, tidak akan mereka biarkan aku berada di belakang, bahkan tulang-tulangku.
“Tidak ada yang memerintahku di pusara kematian oppungku. Aku memiliki kompasku sendiri,” Tambahku, ku temui kedua mata raja yang tidak mengenaliku itu, ia memalingkan pandangannya, sejauh itu, tidak ada yang menjawabku. Pertemuan di majelis itu berakhir saat Oppung boruku semakin tajam dalam ratapannya.
Pesta kematian Oppungku berlangsung beberapa hari, pusaranya tak jauh dari belakang rumah kami, menghadap ke arah bukit yang ia tanami kopi dan pohon durian sewaktu masih hitam surai kepalanya, di sekitar pekuburannya terdapat ladang jagung, dan beberapa petak tanaman lain yang siap panen, jika bukan karena pengepul-pengepul yang serakah, sejahteralah seluruh masyarakat di kampung yang begitu cakap sistem pengairannya itu.
Pigura dengan lukisan wajah Oppungku yang dulu kubuatkan sewaktu menyusuri jurang kepalaku di Jakarta, membuatku tak kuasa berdiri, tak ada air mata, hanya ingin memberikan rasa hormatku yang begitu dalam padanya untuk kali terakhir, sebab kutahu tak mudah datang ke tempat ini di hari yang akan datang walau masih hidup Oppung boruku, lebih mudah ke negeri yang lain, pikirku. Kukeluarkan beberapa lembar Napuran[15], pining[16], dan hapur[17], aku bungkus menjadi satu dengan selembar sirih yang lain untuk kumakan, kunyalakan sebatang rokok kretek, kunikmati Napuran dan kretek itu di depan makam Oppungku, tak banyak yang kupikirkan, suara-suara burung yang berasal dari atas bukit terdengar sampai ke telingaku, matahari sudahlah mulai tertutup dengan awan mendung, bersamaan dengan suara guruh yang tidak mengenal malu,
“Bang,” Panggil Mamak, ia datang dari arah rumah.
“Iya, Mak,” Sahutku. Masih dikenakannya sebuah Ulos[18] melingkari pundaknya,
“Sudahkah rindu?”
“Tidak,” Kataku
“Mereka sudah lupakan Oppungmu, sudah pula tawa-tawa nyaring terdengar dari perut mereka yang terisi kerbau, kuda, dan babi. Hanya amplop-amplop di saku mereka yang membuat mereka sedikit teringat kembali. Tiada tahu diri kita orang batak ini terhadap guru, dan kematian mereka. Sial memang kematian tua-tua orang batak itu, bahkan di rintik air mata yang berserakan di rumah-rumah orang mati, hanya ringgit yang mereka pikirkan sampai terlelap tidur nanti, semua soal seberapa berharganya perak, sedikit pula yang memperhatikan hidup orang yang sudah terkubur ini, dengan nilai-nilai yang Oppungmu tinggalkan,
Beginilah aku sebab ajar dari Oppung dolimu, bijaklah dia sejak dahulu, luka di wajahku ini jadi saksi betapa aku tidak kenal curiga di masa mudaku, luka ini pula yang membuat Oppungmu berlari dengan kakinya yang tidak imbang dari persawahan, yang dalam tangisnya lahir ribuan riwayat untuk anak perempuannya ini agar tak boleh mengambil kegamangan.
Bapakmu tak menemaniku, itu pilihannya, tak boleh kau salahkan dia dan keluarganya, itu yang Oppungmu ajarkan juga, sudah kau dengar itu ribuan kali pula. Kusampaikan ini agar tenang hatimu, agar tak jadi berarus isi kepalamu.” Mamak berdiri di sampingku, ia lihat papan kayu dengan nama muda Oppungku dan cucu laki-lakinya dari tulangku yang pertama, itulah yang tertulis di sana, walau aku adalah yang tertua di antara semua cucu-cucu Oppungku, bukanlah namaku yang terukir di bawah nama mudanya itu, sebab yang datang kedualah Mamakku dari anak-anak Oppungku. Bagiku bukan masalah yang cukup besar nama itu, hanya sedikit menggangguku, cucu laki-laki oppungku yang lain tidaklah sama denganku, mereka adalah pelupa bersama orangtua-orangtua mereka, yang mencintai oppungku saat masih bisa berikan mereka upah dari panggilan mereka, jika datang tanda-tanda alam, mereka katakan itu adalah kerinduan Oppungku, namun itulah rasa penyangkalan mereka saat masih hidup Oppung doliku itu. Tak mereka biarkan kematian tenang dengan takhayul-takhayul yang muncul dari ketakutan mereka menerima hidup, yang muncul juga karena rasa bersalah mereka sebab tak mereka dampingi nilai-nilai melawan yang Oppung doliku ajarkan untuk menghidupi hidup, agar jadilah manusia benar-benar sejati di langkah-langkah kecil mereka. Siallah memang, Pikirku mendengar perkataan Mamak.
Hujan turun, Mamak menarik tanganku, mati kretek yang menempel di bibirku yang memerah karena Napuran, kami berjalan di tengah kebun jagung di bawah hujan yang sudah mengingatkanku akan kehadirannya sejak tadi, sedikit tumpah air mataku, disembunyikan derasnya hujan sore itu, karena kulihat pula Mamak yang menarik tanganku, meletakkan Ulos yang tadi ia kenakan di atas kepalaku, ia tak pikirkan dirinya di tengah kesedihannya, saat itu ia menjadi seorang ibu, kawan, dan peraduanku yang hening, kepeduliannya adalah tanda perlawanan, kata-katanya juga, ditambah sikap-sikap yang ia pilih, bukan karena aku anaknya, tapi karena ia adalah seorang Ibu, Perempuan, yang menjaga dan menjalankan gagasan tak kenal takutnya, yang menjaga dirinya–ditemani warna-warna api.
Itulah, Mamakku. Perempuan yang menghimpun kehendak-kehendak Perlawanan, dari sedikitnya tulisan yang mampu kutulis mengenai dirinya di buku tidurku, dengan banyak air mata di bagian sampulnya, yang tak berani mengarah masuk ke dalam kertas-kertas lemah yang terdorong oleh sorak-sorai tinta-tinta bernuansa hitam, agar melupakan seberapa mudah berlubangnya mereka lantaran terurai jatuh air mata.
Bagian Satu,
Mamak, Kawanku.
Bagian dua, akan kucuri lagi dari Phronrhutēr.
[1] Sianjur Mula Mula, Kecamatan di Samosir.
[2] Oppung, Kakek atau Nenek dalam bahasa Toba. Oppung Doli; Kakek
[3] Amang, sebutan Bapak dalam bahasa Toba.
[4] Andaliman adalah sebutan untu merica Batak.
[5] Sirias merupakan kecombrang dalam bahas Toba.
[6] tulang: paman dari garis ibu.
[7] Capsaicin, senyawa kimia yang terdapat dalam cabai, memberikan rasa pedas.
[8] Kuwah beulangong, masakan tradisional Aceh berupa gulai daging.
[9] Boru, sebutan untuk anak perempuan dalam bahasa Toba
[10] raja, merujuk pada keluarga laki -laki perempuan, dalam hal ini ayah.
[11] Parumaen, sebutan untuk Menantu.
[12] raja – raja merujuk pada pemimpin-pemimpin adat.
[13] Nantulang, sebutan untuk istri paman dari sisi ibu.
[14] Pariban merupakan sebutan untuk sepupu perempuan dari sisi ibu.
[15] Napuran: sirih
[16] Pining: pinang
[17] Hapur: kapur sirih
[18] Ulos, kain tenun tradisional khas batak.