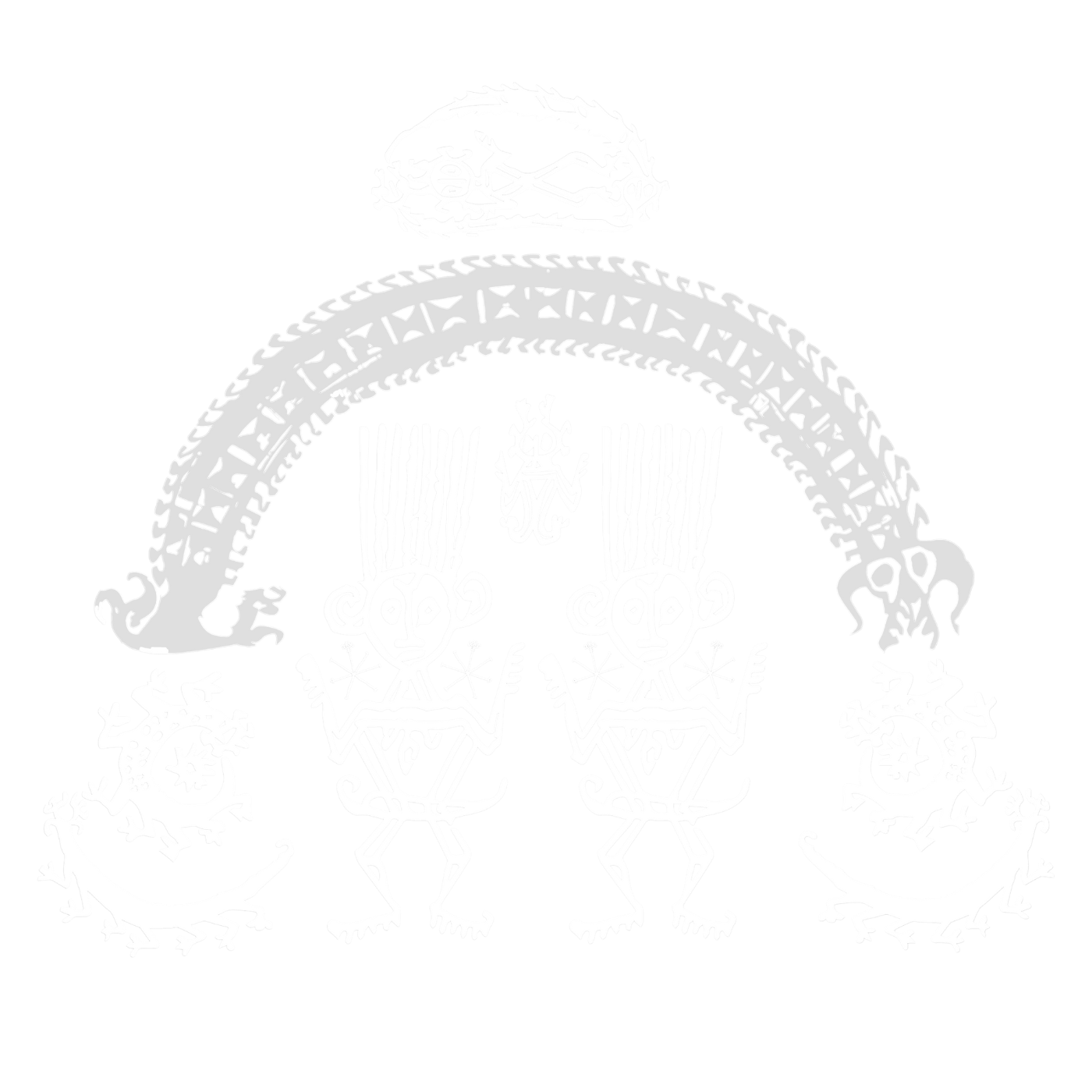Simulacra merupakan salinan atau representasi yang tidak lagi memiliki acuan pada realitas. Simulacra adalah Tanda yang dipisahkan dari kebenaran dan kenyataan yang awalnya diungkapkan. Otentisitas dalam hal ini – merujuk pada Cyberspace sering kali merupakan konstruksi yang telah direduksi atau bahkan direkayasa.
Sementara itu Hyperreality adalah keadaan di mana perbedaan antara realitas dan representasi menjadi tidak jelas, sehingga menghasilkan sebuah “realitas” baru yang lebih dominan dibandingkan kenyataan itu sendiri. Hyperreality muncul ketika Simulacra mengambil alih realitas, menciptakan pengalaman yang dianggap lebih nyata daripada yang nyata. Untuk itu Konsep ini mampu memberikan pemahaman atas Dunia Digital atau Cyberspace yang penuh dengan citra dan informasi yang disusun secara strategis.
Realitas atau Ilusi
Media Sosial menjadi tempat di mana Simulacra tumbuh dengan Cepat. Konten – konten yang diunggah di platform seperti Instagram atau Tiktok sering kali dicitrakan sebagai gambaran ideal kehidupan, yang tidak selalu mencerminkan kenyataan. Seperti yang dijelaskan oleh Jean Baudrillard, Seorang Filsuf asal Prancis yang kemudian memberikan pemahaman atas gagasan ini. Representasi tidak hanya menutupi realitas, tetapi juga membentuknya—sebuah dunia digital di mana “asli” dan “tiruan” saling berbaur.
Dengan adanya kemudahan dalam mengakses informasi dan interaksi digital, muncul pertanyaan penting “Apakah dunia yang kita alami melalui layar di hadapan kita benar-benar nyata?” Diskusi ini menyoroti kontradiksi antara pengalaman langsung dan representasi digital. Beberapa filsuf berpendapat bahwa digitalisasi mampu memperkuat realitas, Namun Baudrillard mengingatkan bahwa representasi tersebut dapat menggantikan keaslian, sehingga membingungkan batas antara yang nyata dan imajinasi.
Kecemasan, Keterasingan dan Autentisitas
Fenomena simulacra dan hyperreality menghadirkan dilema etis dan eksistensial yang kompleks. Dengan meningkatnya dominasi pengalaman digital, muncul perasaan keterasingan dan krisis identitas, di mana nilai autentisitas sering kali diabaikan. Baudrillard menantang kita untuk perlu bersikap kritis terhadap pengaruh representasi digital dalam membentuk persepsi diri, serta mempertanyakan konsep-konsep tradisional mengenai kebenaran dan realitas.
Menurut survei yang dilakukan oleh World Health Organization, Sekitar 40% remaja mengalami kecemasan akibat konten – konten yang dikonsumsi melalui Sosial Media. Dalam dunia hiperrealitas, kita tidak lagi menjadi produsen makna, melainkan konsumen tanda yang pasif. Akibatnya, kita mengalami alienasi dari tubuh, emosi, dan hubungan yang sejati, terperangkap dalam lingkaran Interaksi sosial yang didominasi oleh Gimick.
Saat ini kita berada di mana algoritma membentuk kampanye pemilu, dan aktivisme telah direduksi menjadi clicktivism, dan kekuasaan beroperasi melalui penciptaan tanda, Kita tidak lagi Mencipatakan Makna hidup, melainkan sebagai Konsumen yang terperangkap dalam siklus simulasi.
Media Sosial sebagai Panggung Politik Hiperreal
Media sosial telah menjadi Koloseum di mana Politik Identitas dan kekuasaan direkonstruksi sebagai Konsumsi Primer. Hal ini mengungkap bagaimana Figur Politik seperti Prabowo di Tiktok tidak lagi merepresentasikan individu nyata, melainkan Produk yang dikurasi melalui algoritma untuk memproduksi Emosi Kolektif. Hal ini merupakan “Politic on the Edge of Death.” Kekuasaan tidak lagi mengontrol realitas fisik, tetapi menciptakan mitos-mitos digital yang dikonsumsi sebagai sebuah kebenaran. Di sisi lain Aktivisme pun terjebak dalam paradoks, tagar yang menyebar luas hanya diikuti sedikit partisipasi fisik dalam demonstrasi nyata. Gimmick Klik dan share kemudian menjadi Liturgi Sesat yang memberi ilusi partisipasi, sementara struktur kekuasaan nyata tetap tak tercerahkan.
Pemilu dalam Cengkeraman Simulasi
Demokrasi Modern telah menjadi “Praktik yang kehilangan substansi”. Algoritma mendorong untuk menciptakan Kandidat dengan pidato yang dirancang sempurna untuk memanipulasi emosi pemilih. Microtargeting berbasis data mengelompokkan pemilih ke dalam “realitas alternatif” yang dipersonalisasi, di mana kebenaran objektif digantikan oleh narasi algoritmik. Pemilih tidak lagi memilih platform politik, tetapi ditetapkan atas Figur Hiperreal yang dikonstruksi melalui kombinasi data dan rekayasa citra. Dalam hiperrealitas, pilihan kita adalah keputusan palsu yang telah diprediksi oleh mesin.
Aktivisme, Antara Revolusi dan Pasivitas yang Terkurasi
Aktivisme di era Cyberspace sering kali terperangkap dalam logika hiperrealitas. Social Issue menjadi konten dramatis yang terlihat Seksi untuk dikonsumsi dan dibagikan, lalu dilupakan begitu algoritma media sosial mengalihkan perhatian ke isu lain yang Sedang Happening, yang kemudian menguntungkan secara insight untuk basis data mengembangkan Persona. Fenomena ini mencerminkan apa yang kita sebut sebagai “kelelahan masyarakat spektakel.” Kita terus-menerus terstimulasi oleh tanda-tanda perlawanan, tetapi kehilangan energi untuk aksi nyata. Bahkan gerakan sosial terus berkompromi dengan logika platform—revolusi menjadi produk, melalui desain visual yang menarik dan durasi konten yang singkat. Sembari menyelami kenyamanan Pasivitas Kita menjadikan simbol-simbol perubahan sebagai Berhala yang wajib disembah.
Kolonialisme Digital
Trend di TikTok dan Instagram melebihi ekspektasi dasar kita. Dan sering kali menjadi Alat normalisasi tindakan Politik. Di Negara bekas jajahan – Negara Dunia Ketiga seperti Indonesia hal ini dipromosikan sebagai Estetika Digital. Tren “Presiden Baik” Menciptakan Citra Tegas dan Berwibawa, sampai mengabadikannya menjadi Kepemimpinan Fundamental atas Negara. Hal ini merupakan bentuk “Symbolic Violence.” Eksistensi kita diubah menjadi sebatas Angka untuk kekuasaan melanggengkan hierarki sosial mereka melalui kode digital.
Demokrasi Algoritmik
Tribun digital atau Platform telah melahirkan bentuk kekuasaan baru, pemerintahan bayangan yang dijalankan oleh algoritma. Filter Buble mengurung pengguna dalam ruang gema politik, di mana perbedaan pendapat direduksi oleh mekanisme Content Recommendation. Sebagai contoh, di Indonesia, secara tak sadar kita telah memperkuat narasi hiperreal Presiden dan Wakil Presiden yang Berkelanjutan, yang kemudian berujung pada masalah – masalah lain yang lebih kritis di masa yang akan datang . Kekuasaan sejati adalah yang tidak terlihat, karena ia telah menyatu dengan sistem tanda yang kita konsumsi setiap hari. Kemudian melahirkan Generasi yang percaya bahwa “Bergerak tidak mengubah apapun,” adalah korban dari demokrasi yang telah kehilangan tempatnya, kemudian teralienasi oleh simulasi korup dan ketidakadilan yang terus terulang di hadapan kita, – layar.
Membongkar Hiperrealitas
Untuk Keluar dari labirin Hiperrealitas kita memerlukan kesadaran kritis yang radikal. Pertama –Tama , kita perlu membongkar spectacle dengan mengekspos struktur mekanis di balik Viralitas dan melakukan kurasi algoritmik. Kemudian, membentuk kembali aksi politik embodied—kehadiran fisik dalam aktivisme dan aksi, Mengorganisir Masa, atau pendidikan literasi yang berkelanjutan, Sebagai penangkal Pasivitas. Selanjutnya, melakukan subversi kreatif terhadap platform, bagaimana algoritma bisa dibalik untuk mengganggu narasi dominan. Di era ini, revolusi sejati adalah menolak berpartisipasi dalam siklus produksi tanda. Kita harus menjadi Pemilik atas Makna, dan Menciptakan Makna itu di tengah tanah tandus Simulasi, sehingga kemudian tidak lagi menjadi penonton dalam panggung Hiperrealitas yang kita bangun sendiri selama ini.