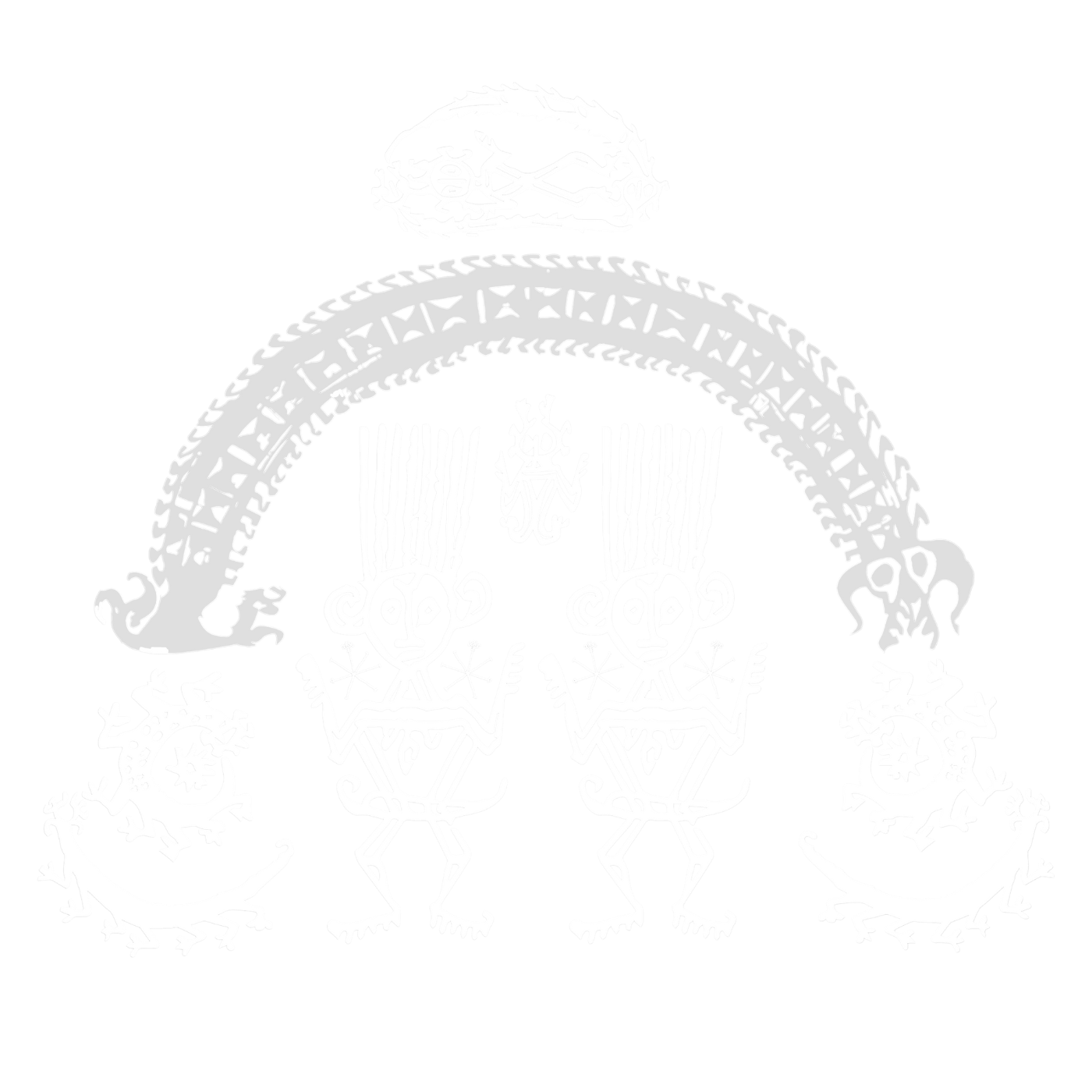Kita adalah Pelupa—bukan karena disebabkan defisiensi neurologis, melainkan hadirnya negara yang kemudian menjadi kutukan terhadap ingatan kolektif kita. Pelupaan merupakan proyek politik yang disengaja, upaya sistematis untuk mengaburkan memori kolektif atau menghapus jejak-jejak kekerasan yang telah dilakukan oleh negara. Negara tidak hanya mengatur tubuh dan ruang, tetapi juga memaksa masyarakat untuk memproduksi lupa, yang kemudian melahirkan perubahan pada gagasan dan narasi menjadi komoditas sebagai aspek bernilai tukar. Henri Lefebvre dalam esainya The Production of Space menulis bahwa setiap masyarakat memproduksi ruangnya sendiri, namun dalam proses itu, masyarakat turut memproduksi lupa. Mekanisme kekuasaan negara tidak hanya sekadar mengontrol, namun layaknya Leviathan, mencengkeram dengan begitu kuat—dan tentu, harus segera dihancurkan.
Dalam hal ini ‘lupa’ merupakan konstruksi kepatuhan yang dipaksakan melalui kekerasan struktural, sebuah mekanisme yang membuat kita akhirnya menganggap kemiskinan, sistem pendidikan yang kacau, sadisme yang dipertontonkan oleh perangkat negara, perampasan tanah, dan berbagai ketidakadilan lainnya sebagai sesuatu yang wajar. Pada akhirnya—kita diarahkan pada penerimaan takdir.
Max Weber mendefinisikan negara sebagai entitas yang memiliki legitimasi atas penggunaan kekerasan. Hal ini seharusnya menjadi renungan kita, melihatnya sebagai bukan hanya sekadar monopoli kekuasaan, tetapi mekanisme yang menekan kebebasan individu serta memanipulasi ingatan kolektif demi menjaga dominasi. Russell Jacoby dalam bukunya Social Amnesia: A Critique of Contemporary Psychology menjelaskan bahwa secara umum kehilangan ingatan tidak dapat dijelaskan hanya melalui aspek psikologis, tetapi juga merupakan kelupaan kolektif—yakni ingatan yang terpinggirkan akibat dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Hal itu mempertegas bahwa lupa kolektif merupakan hasil dari struktur yang sengaja negara ciptakan untuk menjaga kedudukannya.
Senjata Kuasa yang merampas Ingatan
Negara, sebagai mesin penindas, telah melakukan kekerasan sistematis dalam kurun waktu yang begitu panjang untuk mempertahankan kontrol atas kekuasaan.
Pembunuhan massal pada 1965-1966 menargetkan anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui kebijakan antikomunis. Akibatnya, sekitar 500.000 hingga 1 juta orang menjadi korban pembunuhan oleh militer, puluhan ribu orang ditahan tanpa proses peradilan yang jelas, dan penghilangan paksa terjadi dalam jumlah yang tak terhitung. Sejak 1969, Papua menjadi sasaran operasi militer yang menewaskan ratusan ribu orang. Dalam dekade terakhir, tercatat 15.000 korban akibat operasi ini, dan puluhan ribu masyarakat adat tergusur dari tanah mereka akibat kontrol teritorial negara. Tidak berhenti sampai di sana, kemudian negara melakukan kontrol atas tanah masyarakat adat, salah satu dari banyaknya kasus perampasan tanah dan wilayah adat yang dilakukan oleh negara, perampasan tanah adat terjadi di hutan adat masyarakat Awyu dan Moi, yang menyebabkan deforestasi seluas 663.443 hektare. Deforestasi ini semakin parah pada masa pemerintahan Joko Widodo.
Puncak gejolak masyarakat terjadi pada Mei 1998. Suharto, yang berkuasa selama 32 tahun, menolak tunduk kepada rakyat dan berupaya mempertahankan kekuasaan melalui berbagai bentuk kekerasan. Tragedi ini menewaskan 1.300 orang, 27 di antaranya akibat senjata aparat, empat diantaranya termasuk penembakan di Trisakti—di mana empat mahasiswa menjadi sasaran tembak mati aparat saat melakukan aksi unjuk rasa. Kekerasan seksual juga menjadi kasus yang belum terselesaikan hingga kini. Pada 1997-1998, banyak kasus penghilangan paksa dilaporkan, namun tidak pernah diusut tuntas. Bahkan, terduga otak di balik kasus-kasus tersebut, Prabowo Subianto, terpilih sebagai presiden untuk periode 2024-2029.
Kematian tahunan akibat kelaparan dan penyakit, yang mencapai ribuan orang, merupakan bentuk kekerasan struktural yang digunakan negara sebagai alat kontrol kekuasaan. Negara juga secara bertahap mengendalikan pendidikan, menyebabkan kemerosotan. Alih-alih mengatasi masalah ini, negara memanfaatkannya untuk mendominasi kemiskinan dan kebodohan demi kebutuhan elektoral.
Kekerasan negara tidak terhitung jumlahnya, bahkan dalam aspek terkecil sekalipun. Negara memanfaatkan kekerasan untuk menciptakan ketakutan, yang melahirkan kepatuhan dan pelupaan. Negara secara sistematis membentuk narasi baru dalam ingatan kolektif melalui pendidikan. Kekerasan yang terjadi digambarkan sebagai hal wajar demi melindungi bangsa. Sementara itu, korban dan keluarga yang terdampak ditanamkan rasa takut melalui pembungkaman dan ancaman. Akibatnya, generasi berikutnya tumbuh dalam keadaan lupa akan sejarah, karena ingatan sejarah telah dirampas dari kehidupan mereka.
**
Dalam kacamata psikoanalisis, melupakan merupakan mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh manusia untuk lepas dari jeratan trauma. Namun, negara justru melihat trauma sebagai senjata politik dalam melanjutkan usaha dominasi, trauma tidak lagi menjadi pengalaman personal, melainkan proyek negara. Elaine Scarry dalam The Body in Pain melihat penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh negara sebagai siasat untuk mengosongkan bahasa atau dominasi narasi, korban kekerasan kehilangan kemampuan mereka untuk menceritakan kembali atau menggambarkan ulang ingatan mereka, masyarakat kemudian kehilangan kemampuan mengingat. Sepanjang tahun 2024-2025 terdapat sejumlah kasus yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Imparsial melaporkan terdapat 41 kasus kekerasan, 67 orang menjadi korban, 17 orang diantaranya meninggal dunia. Komnas Perempuan dalam periode 2020-2024 mencatat 190 pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh tentara. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI) dalam kurun waktu 20-27 Maret 2025 mencatat terdapat 191 korban kekerasan dan 153 penangkapan selama aksi tolak RUU TNI yang dilakukan oleh aparat. Dalam kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat sebagai alat negara yang sampai saat ini terus berlanjut, negara berupaya mengaburkan ingatan kolektif masyarakat dengan pembungkaman, intimidasi, disinformasi, atau memanfaatkan skandal sensasional untuk mengalihkan perhatian masyarakat.
Martin Seligmen dalam teorinya Learned helplessness menjelaskan fenomena di mana ketika seseorang secara berulang dihadapkan pada kekerasan dan penderitaan tanpa bisa melawan dan berkuasa untuk mengatasinya, mereka mulai mempercayai ketidakberdayaan sebagai bagian dari diri mereka. Masyarakat yang setiap hari mendapatkan kabar kekerasan, atau ancaman struktural, secara psikologis terampil untuk pasrah, kemudian terbentuklah narasi kepasrahan di tengah masyarakat, bermula melalui pertanyaan-pertanyaan seperti “Apakah aksi protes akan didengarkan?” atau “Apa gunanya turun ke jalan? Kritik tidak akan membuahkan hasil.” Negara mengubah masyarakat menjadi Homo Sacer—Pribadi yang dapat dibunuh kapan saja tanpa konsekuensi hukum, sekaligus tubuh yang lupa bahwa mereka seharusnya memiliki ekspresi kemarahan.
Negara sebagai Penjara Ingatan dan Kebebasan
Filsafat Barat seringkali dipakai sebagai alat legitimasi pelupaan. Friedrich Hegel, dalam Philosophy of Right menyampaikan soal negara sebagai Ethical Order, seakan-akan kekerasan negara merupakan dampak logis dari kemajuan. Anarkisme menampik narasi ini, seperti yang dijelaskan oleh Mikhail Bakunin dalam God and the State, negara adalah kekuatan, dan karena sifatnya sendiri, kekuatan itu bertentangan dengan kebebasan, negara selalu merupakan warisan dari kelas yang istimewa, dan sebagai akibatnya, selalu merupakan alat untuk eksploitasi dan perbudakan. Ini menunjukkan bahwa negara, sebagai institusi, menyembah kekuasaan dengan cara menguduskan dominasi kelas penguasa. Negara, dalam hakikatnya, adalah penyangkalan kebebasan manusia, dan dalam bentuknya yang paling sempurna, negara adalah penjara terbesar yang pernah diciptakan untuk kemanusiaan, negara adalah penyembahan kekuasaan yang terinstitusionalisasi.
Michel Foucault tentang Biopower menegaskan melalui institusi pendidikan dan media, negara mengontrol bukan hanya kehidupan biologis masyarakat, namun juga kehidupan kognitif mereka. Public policy kemudian menjadi mesin yang menghancurkan narasi kritis, akibatnya adalah masyarakat melupakan bahwa pengetahuan dapat menjadi alat pembebasan.
Kemiskinan, Memelihara ketidakberdayaan
Dalam bukunya La Misère du monde Pierre Bourdieu menuliskan soal kemiskinan yang bukan sekedar keadaan ekonomi, akan tetapi kekerasan simbolik yang merampas kebebasan bertindak. Kemiskinan struktural sengaja dipelihara oleh negara—rakyat yang berusaha keras mengisi kebutuhan mereka, tidak akan memiliki energi untuk memberontak. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat 24,06 juta orang, yang setara dengan 8,57% dari total penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan—angka yang kemungkinan besar direkayasa melalui manipulasi statistik. Namun, yang lebih berbahaya dari itu semua adalah normalisasi dari kemiskinan itu sendiri. Program bantuan sosial seperti Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bukanlah solusi, melainkan Political Soporific—bukannya membongkar ketimpangan pada sistem, negara justru memberikan placebo agar masyarakat tetap dalam keadaan tenang walaupun tahu mereka hidup di tengah ketidakadilan.
Bullshit Jobs yang ditulis oleh David Graeber mengaitkan fenomena ini dengan Moralitas Kerja kapitalis, yang menganggap orang harus menderita melalui pekerjaan yang tidak bermakna untuk membuktikan bahwa mereka layak hidup. Orang miskin, kecuali mereka bersedia menjadi budak upah, tidak dianggap layak mendapatkan bantuan. Di Agrentina, misalnya program Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (Program Kepala Rumah Tangga Pengangguran) bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran bukan dengan reformasi struktural, namun dengan menjerat masyarakat dengan bantuan yang bertujuan pada kepatuhan politik. Hal tersebut merupakan bentuk pelupaan terencana—masyarakat dilatih untuk mengabaikan dan melupakan akar kemiskinan mereka, dengan bagaimana mereka dibebani pada cara bertahan hidup untuk hari ini.
Budaya Kepasrahan dan Toxic Positivity
James C. Scott antropolog Amerika dalam Weapons of the Weak menunjukkan bagaimana kelas yang termarjinalkan, melawan penindasan dengan perlawanan sehari-hari, everyday resistance, melalui rumor negatif, penghindaran, pencurian kecil-kecilan, atau pura-pura bodoh. Namun, kemudian senjata kaum tertindas ini dirampas oleh negara melalui budaya toxic positivity. Di Indonesia, negara melalui internet melancarkan kampanye dengan tagar #IndonesiaCerahsebagai lawan aksi #IndonesiaGelap, negara memakai #IndonesiaCerah untuk menutupi sorotan masyarakat terhadap ketakcakapan pemerintahan Prabowo mengatasi berbagai masalah yang muncul sejak kepemimpinannya. Atau bagaimana Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi menanggapi teror pengiriman kepala babi tanpa telinga yang dialami Jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana dengan mengatakan “Sudah dimasak saja”.
Budaya “Nrimo” dalam Jawa bukanlah sekedar kearifan lokal, melainkan sebuah produk feodalisme yang mengalami romantisasi. Nietzsche, dalam terminologinya, menggunakan slave morality—mengubah kelemahan menjadi kebajikan. Negara melalui media masa dengan didukung industri hiburan melakukan pembesaran dan perluasan narasi ini melalui produk-produknya yang menggambarkan kemiskinan adalah bagian dari takdir ilahi yang kemudian menawarkan produk kapital lainnya sebagai solusi kebahagiaan. Pada akhirnya masyarakat lupa bahwasanya kemarahan merupakan reaksi yang sahih terhadap ketidakadilan yang menerpa mereka.
Anarkisme sebagai Antidoton
Anarkisme menawarkan solusi untuk memutus siklus pelupaan atau amnesia sosial ini. Yang paling penting adalah bagaimana tradisi solidaritas yang telah ada tetap terjaga, dan menyerang balik setiap negara menyusupinya dengan narasi nasionalisme di setiap kesempatan, sebagaimana masyarakat adat berperan besar terhadap tradisi solidaritas—seperti Marsiadapari di tanah Batak, Subak di Bali, Mappandesasi di tanah Mandar—sebelum dihancurkan oleh negara dengan narasi nasionalisme yang berbau busuk. Dengan itu pula kemudian terciptalah masyarakat alternatif, sampai menunggu waktu revolusi besar terjadi. Contohnya, komunitas Squatting di Amsterdam atau gerakan ZAD (Zone à Défendre) di Prancis yang menempati lahan-lahan kosong untuk membangun ekonomi mandiri.
Namun, yang lebih penting lagi, dan harus dilakukan dengan cara radikal adalah bagaimana upaya untuk mengembalikan ingatan yang telah dirampas oleh negara. Dalam Anarchist Pedagogies, pendidikan menekankan praktik dekolonisasi ingatan. Seperti Escuela Moderna yang didirikanFrancisco Ferrer pada 1904 di Barcelona, Zapatista di Chiapas, Gerakan Mapuche di Chili dan Argentina, Komune Rojava di Suriah Utara—yang menekankan pendidikan otonom, media independen, dan peringatan kolektif. Di Indonesia, Inisiatif Anarkis sering kali berupaya melakukan bermacam-macam pendekatan untuk mengembalikan ingatan kolektif di berbagai tempat, tanpa terbatasi oleh ruang dan waktu. Melalui pendampingan otonom, pendidikan dan publikasi alternatif, riwayat lisan dan peringatan, serta historiografi kritis—memiliki kekuasaan atas narasi untuk menentang narasi lain yang negara ciptakan untuk mengontrol masyarakat, merekonstruksi memori kolektif sebagai basis perlawanan.
Narasi merupakan senjata eminen yang secara fundamental digunakan Anarkis untuk melakukan upaya perlawanan terhadap otoritas dan hegemoni negara yang membodohi dan membatasi masyarakat, demi tercapainya kebebasan lupa atau amnesia sosial. Hal ini pula yang menjadi tantangan bagi masa depan Anarkisme di Indonesia, bagaimana memanfaatkan narasi sebagai senjata utama.
**
Negara ingin kita menghapus ingatan dan melupakan; sementara itu, tugas kita adalah mengingat—tidak hanya sebagai sentimentalitas, tetapi dengan aksi yang berlanjut, menghidupkan dan membangkitkan kembali kenangan atau catatan terhadap ketidakadilan yang menjerat kita. Anarkisme merupakan praktik terapi terhadap lupa, setiap kali kita berbagi makanan di dapur umum, membentangkan permadani dengan buku-buku yang dengan bebas dibaca dan didiskusikan, pamflet-pamflet narasi dengan perekat berbau tidak sedap seperti para bajingan di gedung dewan perwakilan rakyat, dan setiap kemarau yang kita lewati dengan alas kaki yang dibuat di sudut-sudut tertinggal lingkungan kita, adalah gerakan perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas, melawan lupa.
“Anarchism, then, really stands for the liberation of the human mind from the dominion of religion; the liberation of the human body from the dominion of property; liberation from the shackles and restraint of government. Anarchism stands for a social order based on the free grouping of individuals for the purpose of producing real social wealth; an order that will guarantee to every human being free access to the earth and full enjoyment of the necessities of life, according to individual desires, tastes, and inclinations.”
Dalam esainya Anarchism and Other Essays, Emma Goldman mencerminkan gagasan anarkisme mengenai narasi sebagai senjata perlawanan dan ingatan kolektif—yang perlu dipakai dalam setiap kesempatan untuk mempertahankan kebebasan dari kebusukan yang negara ciptakan.
Melawan adalah berkehendak untuk hidup. Arus yang membisikkan kalimat-kalimat pembebasan dari lorong sungai serupa rantai, menuju hilir kebebasan. Ditemani ombak yang tak habis menemani tidur panjang kita, menghadapi belenggu tirani.
Di dalam keheningan yang menjerat kita, kata-kata berwujud api adalah segalanya, mendesis, menjalar ke berbagai rupa, melawan lupa.
Phronrhutēr
Catatan Akhir
Bakunin, M. (1882). God and the State. Mother Earth Publishing.
Bourdieu, P. (1993). La Misère du Monde. Seuil.
Foucault, M. (1976). The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. Pantheon Books.
Goldman, E. (1910). Anarchism and Other Essays. Mother Earth Publishing.
Graeber, D. (2018). Bullshit Jobs. Simon & Schuster.
Haworth, R. H. (Ed.). (2012). Anarchist Pedagogies: Collective Actions, Theories, and Critical Reflections on Education. PM Press.
Hegel, G. W. F. (1821). Philosophy of Right. Clarendon Press.
Jacoby, R. (1975). Social Amnesia: A Critique of Contemporary Psychology. Beacon Press.
Lefebvre, H. (1974). The Production of Space. Blackwell.
Scarry, E. (1985). The Body in Pain. Oxford University Press.
Scott, J. C. (1985). Weapons of the Weak. Yale University Press.
Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On Depression, Development, and Death. W. H. Freeman.
Weber, M. (1919). Politics as a Vocation. Duncker & Humblot.